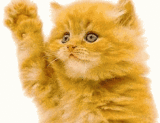Tugas Analisis Kurikulum (UTS 1)
Perkembangan kurikulum di Indonesia
Perkembangan kurikulum diindonesia mengalami beberapa kali perubahan. Yaitu mulai dari kurikulum tradisional atau biasa disebut dengan matematika tradisional,matematika modern,kurikulum matematika 1984,kurikulum matematika 1994, kurikulum 2004 atau yang biasa disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi,dan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan).
1. Matematika Tradisional
Indonesia merupakan Negara yang pernah mengalami penjajahan. Tentunya hal ini membuat system pendidikan menjadi terganggu. Oleh sebab itu, pemerintah bangkit dan memperbaiki system pendidikan di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Matematika pada kala itu merupakan mata pelajaran yang wajib bagi siswa, dan merupakan ilmu hitung dan berhitung. Urutan-urutan materi seolah-olah telah menjadi konsensus masyarakat. Karena seolah-olah sudah menjadi konsensus maka ketika urutan dirubah sedikit saja protes dan penentangan dari masyarakat begitu kuat. Untuk pertama kali yang diperkenalkan kepada siswa adalah bilangan asli dan membilang, kemudian penjumlahan dengan jumlah kurang dari sepuluh, pengurangan yang selisihnya positif dan lain sebagainya. Pada setiap kurikulum pasti memiliki karakteristik, begitu pula dengan matematika tradisional, memiliki karakteristik tersendiri, yaitu pembelajaran lebih menekankan hafalan dari pada pengertian, menekankan bagaimana sesuatu itu dihitung bukan mengapa sesuatu itu dihitungnya demikian, lebih mengutamakan kepada melatih otak bukan kegunaan, bahasa/istilah dan simbol yang digunakan tidak jelas, urutan operasi harus diterima tanpa alasan, dan seterusnya. Pada saat matematika tradisonal Urutan operasi hitungnya adalah kali, bagi, tambah dan kurang. Maksudnya bila ada soal dengan menggunakan operasi hitung maka perkalian harus didahulukan dimanapun letaknya baru kemudian pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Urutan operasi ini mulai tahun 1974 sudah tidak dipandang kuat lagi banyak kasus yang dapat digunakan untuk menunjukkan kelemahan urutan tersebut. Sebagai contoh di bawah ini merupakan penerapan kurikulum matematika tradisional. Ketika ada soal berbunyi 21:7 jawaban dari soal di atas adalah 3. Namun hasilnya akan berbeda ketika kita mengganti menjadi 9+7:7, berdasarkan urutan operasi yaitu bagi terlebih dahulu dikerjakan kemudian operasi penjumlahan. Ketika urutan itu digunakan maka hasilnnya akan menjadi 10. Perbedaan inilah yang menjadi dasar mengapa urutan tersebut tidak tepat.
Sementara itu cabang matematka yang diberikan di sekolah menengah pertama adalah aljabar dan Ilmu ukur (geometri) bidang. Geometri ini diajarkan secara terpisah dengan geometri ruang selama tiga tahun. Sedangkan yang diberikan di sekolah menengah atas adalah aljabar, geometri ruang, goneometri, geometri lukis, dan sedikit geometri analitik bidang. Geometri ruang tidak diajarkan serempak dengan geometri ruang, geomerti lukis adalah ilmu yang kurang banyak diperlukan dalam kehidupan sehingga menjadi abstrak dikalangan siswa.
2. Matematika Modern
Perkembangan kurikulum matematika modern diawali dengan adanya kurikulum 1975. Model pembelajaran matematika modern muncul karena adanya kemajuan tekhnologi. Ciri khas dari kurikulum matematika modern adalah bahwa belajar matematika harus berlandaskan belajar bermakna dan berpengertian (W. Brownel). Hal ini juga di dukung dengan teori Gestalt yang mengatakan bahwa metode menghafal atau drill merupakan metode yang sesuai, dengan catatan jika metode ini diterapkan setelah tertanam pengertian pada siswa. Berdasarkan pada dua hal di atas, sangat memengaruhi perkembangan pembelajaran matematika di Indonesia. Sehingga berbagai kelemahan seolah Nampak jelas, pembelajaran kurang menekankan pada pengertian,kurang adanya kontinuitas,kurang merangsang anak untuk ingin tahu,dan lain sebagainya. Ditambah dengan adanya kemajuan tekhnologi. Sehingga pada akhirnya pemerintah merancang program pembelajaran yang mampu menutupi kelemahan-kelemahan tersebut. Sehingga muncullah kurikulum 1975, dimana matematika memiliki karakteristik sebagai berikut:
a. Memuat topik-topik dan pendekatan baru. Topik-topik baru yang muncul adalah himpunan, statistik dan probabilitas, relasi, sistem numerasi kuno, penulisan lambang bilangan non desimal.
b. Pembelajaran lebih menekankan pembelajaran bermakna dan berpengertian dari pada hafalan dan ketrampilan berhitung.
c. Program matematika sekolah dasar dan sekolah menengah lebih kontinu.
d. Pengenalan penekanan pembelajaran pada struktur.
e. Programnya dapat melayani kelompok anak-anak yang kemampuannya hetrogen.
f. Menggunakan bahasa yang lebih tepat.
g. Pusat pengajaran pada murid tidak pada guru.
h. Metode pembelajaran menggunakan meode menemukan, memecahkan masalah dan teknik diskusi.
i. Pengajaran matematika lebih hidup dan menarik.
3. Kurikulum Matematika 1984
Tahun 1980-an merupakan gerakan revolusi matematika kedua. Walaupun tidak seheboh pada revolusi matematika pertama atau matematika modern. Penyebab revolusi ini diawali dengan adanya kekhawatiran Negara maju dengan pengajaran matematika mereka yang didukung dengan adanya tekhnologi seperti kalkulator dan komputer. Dengan adanya perkembangan tekhnologi di Negara maju tersebut, berpengaruh terhadap perkembangan kurikulum matematika di Indonesia . di dalam negeri di tahun 1984, pemerintah membuat kurikulum baru, yaitu kurikulum 1984. Alasan pemerintah membuat kurikulum tersebut karena adanya sarat materi,perbedaan kemajuan pendidikan antar daerah dari segi tekhnologi,adanya perbedaan kesenjangan antara program kurikulum di satu pihak dan pelaksana sekolah, serta kebutuhan lapangan dipihak lain. Sehingga dengan adanya beberapa problema seperti itu, maka Cara Belajar Siswa Aktif ditekankan pada kurikulum 1984 tersebut. Hal inilah yang menjadi ciri khas dari kurikulum 1984. Dalam kurikulum ini siswa siswi yang berada pada tingkat sekolh dasar diberikan materi Aritmetika Sosial sementara yang berada di sekolah atas diberikan pelajaran berupa komputer. Hal lain yang menjadi perhatian dalam kurikulum tersebut, adalah bahan bahan baru yang sesuai dengan tuntutan di lapangan, permainan geometri yang mampu mengaktifkan siswa juga disajikan dalam kurikulum ini.
Sementara itu langkah-langkah agar pelaksanaan kurikulum berhasil adalah melakukan hal-hal sebagai berikut;
a. Guru supaya meningkatkan profesinalisme
b. Dalam buku paket harus dimasukkan kegiatan yang menggunakan kalkulator dan computer
c. Sinkronisasi dan kesinambungan pembelajaran dari sekolah dasar dan sekolah lanjutan
d. Pengevaluasian hasil pembelajaran
e. Prinsip CBSA di pelihara terus
4. Kurikulum Matematika 1994
Matematika merupakan kegiatan yang sangat popular di tahun 90-an. Dimana pada saat itu sering dilaksanakan olimpiade matematika. Dalam kurikulum 1994, pembelajaran matematika mempunyai karakteristik. Struktur materi sudah disesuaikan dengan psikologi perkembangan anak, materi keahlian tekhnologi seperti computer semakin mendalam, model pembelajaran matematika kehidupan ditampilkan dalam berbagai pokok bahasan. Intinya pembelajaran matematika pada kurikulum ini menomorsatukan tekstual materi namun tidak melupakan konsep kontekstual yang berkaitan dengan materi, banyak soa cerita disajikan dengan tampilan yang lebih menarik dan mengasah anak.
5. Kurikulum Berbasis Kompetensi
Kurikulum 2004 dirancang dan dikeluarkan oleh pemerintah karena pola-pola lama bahwa guru menerangkan konsep, guru memberikan contoh, murid secara individual mengerjakan latihan, murid mengerjakan soal-soal pekerjaan rumah hanya kegiatan rutin saja disekolah, sementara bagaimana keragaman pikiran siswa dan kemampuan siswa dalam mengungkapkan gagasannya kurang menjadi perhatian. Oleh karena itu kemapuan siswa untuk mengkomunikasikan kelebihannya menjadi terbatas, dan membuat anak enggan mengasah kreativitasnya. Oleh karena itu dikeluarkanlah kurikulum 2004 atau yang dikenal dengan sebutan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Dimana ciri khas dari kurikulum ini yaitu terdapat tiga aspek yang menjadi penilaian. Yaitu aspek kognitif,avektif,dan psikomotor. Dimana kognitif adalah penilaian terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, avektif yaitu bagaimana tingkah laku siswa dan psikomotor yaiu penerapannya terhadap hasil dari pengetahuannya tersebut. Tujuan dikeluarkannya KBK oleh pemerintah yaitu:
a. Melatih cara berfikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksperimen, menunjukkankesamaan, perbedaan, konsistensi dan inkonsistensi
b. Mengembangkan aktifitas kreatif yang melibatkan imajinasi, intuisi, dan penemuan dengan mengembangkan divergen, orisinil, rasa ingin tahu, membuat prediksi dan dugaan, serta mencoba-coba.
c. Mengembangkan kemampuan memecahkan masalah
Mengembangkan kewmapuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan antara lain melalui pembicaraan lisan, catatan, grafik, diagram, dalam menjelaskan gagasan.
6. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memiliki syarat yang dijadikan prinsip menurut(BSNP, 2006: 5 – 7), yaitu :
1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan.
2. Beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.
3. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu semangat dan isi kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan.
5. Menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.
6. Belajar sepanjang hayat. kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal dan informal, dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.
7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengembangan kurikulum ktsp ini juga memiliki pilar-pilar yang harus dipenuhi sesuai dengan tujuan dari kurikulum tersebut. Dimana keenam pilar itu adalah Learning to Know, Learning to Do ,Learning to Be,Learning to Live Together ,Learn How to Learn ,Learning Throughout Life.
Selain itu terdapat pula, dan terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi yaitu Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya, Beragam dan terpadu, Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Relevan dengan kebutuhan kehidupan Menyeluruh dan berkesinambungan. Belajar sepanjang hayat Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
Matematika sekolah merupakan matematika yang diterapkan di sekolah yang memiliki tujuan untuk memahami,menggunakan,memecahkan,mengkomunikasikan, dan memiliki sikap memahami terhadap matematika. Dalam pmbelajaran matematika ada cara belajar, yaitu deduktif, dan induktif. Dalam matematika di sekolah memiliki dan mengikuti SK dan KD serta SKL yang dapat memudahkan siswa.
Sebagai guru kita harus dapat membuat silabus dan rancangan pembelajaran untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan.
DAFTAR PUSTAKA
Dakir, H. 2004. Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Hudojo, Herman. 1979. Pengembangan Kurikulum Matematika dan Pelaksanaannya di Depan Kelas. Surabaya: Usaha Nasional.
http://wikipedia.org/wiki/kurikulum_tingkat-satuan_pendidikan (diakses tanggal 24 Maret 2012)
Senin, 26 Maret 2012
Diposting oleh ratihpenyayangmonyet di 21.10 0 komentar
Rabu, 14 Maret 2012
Lingga
Semua murid terpana melihat makhluk cantik yang berdiri di hadapan mereka. Makhluk itu adalah murid baru di kelas XII IPA 2. Dari sekian banyak murid yang terpana itu, hanya satu dari mereka yang tidak peduli dengan kehadiran makhluk itu. Siswa itu adalah Pralingga. Dia memang tidak pernah tertarik dengan hal-hal yang terjadi di dalam kelasnya. Dia merupakan murid kutu buku dan jarang bergaul dengan teman-temannya. Hal ini Lingga lakukan karena merasa jera dengan teman-temannya dulu ketika Lingga bersekolah di Sekolah Dasar dulu. Saat itu terjadi peristiwa yang sangat pahit yang menerpa hidupnya. Lingga tidak menyangka jika hal itu dapat terjadi pada dirinya. Ketika itu Lingga memiliki seorang sahabat yang bernama Rara. Lingga dan Rara bersahabat sejak SD. Lingga selalu bersama Rara. Setiap orang yang kenal dengan mereka tidak heran jika melihat dimana ada Rara disitu juga ada Lingga. Mereka merupakan sahabat yang sangat akrab. Jalinan persahabatan mereka putus ketika kecelakaan terjadi pada diri Lingga. Kejadian itu terjadi 8 tahun yang lalu, dimana saat itu Lingga berada di kelas III SD. Saat itu Lingga dan Rara pulang sekolah bersama, hal ini memang sering mereka lakukan. Seperti biasa Lingga menggandeng tangan Rara, hal ini Lingga lakukan karena dia ingin melindungi sahabat yang dia sayangi. Ketika itu Rara merasa haus dan meminta Lingga untuk membelikannya es. Lingga menerima permintaan Rara. Lingga dan Rara akhirnya memutuskan untuk membeli es di warung Bi Yun yang berada di seberang jalan,warung yang memang biasa mereka singgahi jika mereka lelah. Ketika Rara melepaskan tangannya dari gandengan tangan Lingga, Rara segera berlari ke seberang untuk membeli es. Namun, dari jarak tidak jauh ada sebuah mobil yang melaju sangat cepat, Rara yang ketakutan berdiri diam. Lingga yang melihat Rara langsung mendorong Rara. Hal itu membuat Rara selamat, tapi tidak dengan Lingga, salah satu kaki Lingga terjepit ban mobil tersebut. Warga yang melihat kejadian itu, segera menolong mereka dan meminta pertanggung jawaban kepada si pengendara. Lingga akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Ibu dan segera di operasi karena keadaan kaki Lingga tak dapat ditolong lagi. Atas persetujuan, akhirnya Lingga dioperasi. Kecelakaan itu membuat Lingga cacat, dia hanya bisa berjalan dengan satu kaki karena Lingga harus kehilangan kaki kanan miliknya. Semenjak Lingga menjalani masa perawatan, ia tidak pernah sama sekali melihat Rara. Menurut cerita Ibunya, Rara dan keluarganya pindah ke Bogor karena Ayahnya mendapat tugas dinas di sana. Lingga sangat sedih mendengar cerita itu, hari-hari yang dijalaninya terasa hampa tanpa Rara. Sekarang dia pulang sekolah sendiri tanpa ada seorang sahabat disampingnya.
Ada satu hal yang baru diketahui Lingga setelah dua minggu Rara pergi. Lingga mendengar kabar ini dari salah seorang tetangganya yang mendengar ucapan Ayah Rara saat mereka ingin pindah ke Bogor. Pak Buni, tetangga Lingga mengatakan jika kepergian Rara ke Bogor itu bukan karena Pak Gorge mendapat tugas di sana, melainkan karena tidak mau anaknya berteman dengan Lingga. Mendengar itu, hati Lingga sangat sakit, dia tidak menyangka orang tua sahabatnya itu berfikiran negative padanya. Tetapi Lingga tidak pernah membenci Rara dan keluarganya.
Kehidupan Lingga menjadi sepi dan tidak bahagia semenjak Rara pindah, hal yang dilakukan Lingga setiap hari hanya membaca buku di kamar dan hanya keluar jika butuh sesuatu. Lingga malu untuk keluar rumah dengan keadaannya yang memakai kursi roda. Lingga malu dengan orang-orang sekitarnya. Begitu pula di sekolah, Lingga hanya diam di kelas dan menjadi pendiam. Lingga jarang bahkan tidak pernah bicara jika temannya tidak mengajaknya bicara duluan. Lingga hanya berbicara jika tidak mengerti dengan pelajaran yang dijelaskan dan menjawab soal yang diberikan oleh Ibu Guru. Meskipun memiliki sifat yang berubah kaku seperti itu, Lingga termasuk murid pandai, dia selalu menjadi juara kelas.
“Anak-anak perkenalkan ini Rara, dia murid baru pindahan dari SMA Negeri 1 Bogor, Rara silahkan duduk di sebelah sana”. Ibu guru Cantika menyuruh Rara duduk di sebelah Lingga. Sebelah bangku Lingga memang selalu kosong, tidak ada seorang murid yang mau duduk dengannya karena sikap Lingga yang dingin dan cuek.
Diposting oleh ratihpenyayangmonyet di 23.03 1 komentar
Label: cerpen
Selasa, 08 November 2011
Tugas UTS Interaksi dan Strategi Belajar Mengajar Matematika
SOAL
1. Jelaskan tujuan pendidikan yang pertama kali dikenalkan oleh Benjamin. S. Bloom serta proses kognitif yang diperkenalkannya!
2. Jelaskan Karakteristik matematika sebagai ilmu yang terstruktur, dan sebutkan unsur-unsur dalam struktur matematika!
3. Apakah definisi Aksioma, Postulat, Dalil, dam Teorema!
4. Menurut anda apa saja masalah yang dihadapi dalam Pembelajaran matematika di sekolah, bagaimana cara menghadapinya?
5. Jelaskan 4 tahap perkembangan kognitif dari individu menurut Piaget!
6. Apa perbedaan antara belajar dan pembelajaran, berikan satu contoh kasus belajar dan satu contoh kasus pembelajaran!
7. Sebutkan dan jelaskan teori belajar aliran psikologi tingkah laku!
8. Pada sebuah sekolah kelas VII SMP dengan siswa berjumlah 30 siswa akan diajarkan tentang konsep perbandingan yang berkaitan dengan skala, jarak dan kecepatan. Sebutkan dan jelaskan metode pembelajaran yang cocok dipakai dalam kelas ini, sebutkan dan jelaskan model pembelajaran yang menarik dipakai pada kelas ini, buatlah langkah-langkah pembelajaran yang mungkin dilakukan!
9. Menurut anda bagaimana perkembangan pembelajaran matematika disekolah, dan tantangan apa saja yang mungkin dihadapi baik dari segi input, proses, output maupunsistempendidikan di Indonesia!
10. Jelaskan Kompetensi standar yang harus dimiliki oleh seorang guru matematika, baik pedagogik, profesi, sosial, dan pribadi!
JAWABAN
1. 1. Tujuan pendidikan pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956. Dalam hal ini, tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain (ranah, kawasan) dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hirarkinya.
Tujuan pendidikan dibagi ke dalam tiga domain, yaitu:
Domain Kognitif
Bloom membagi domain kognisi ke dalam 6 tingkatan. Domain ini terdiri dari dua bagian: Bagian pertama berupa adalah Pengetahuan (kategori 1) dan bagian kedua berupa Kemampuan dan Keterampilan Intelektual (kategori 2-6)
Pengetahuan (Knowledge)
Berisikan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip dasar, dsb. Sebagai contoh, ketika diminta menjelaskan manajemen kualitas, orang yg berada di level ini bisa menguraikan dengan baik definisi dari kualitas, karakteristik produk yang berkualitas, standar kualitas minimum untuk produk, dsb.
Aplikasi (Application)
Di tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, dsb di dalam kondisi kerja. Sebagai contoh, ketika diberi informasi tentang penyebab meningkatnya reject di produksi, seseorang yg berada di tingkat aplikasi akan mampu merangkum dan menggambarkan penyebab turunnya kualitas dalam bentuk fish bone diagram.
Analisis (Analysis)
Di tingkat analisis, seseorang akan mampu menganalisa informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya, dan mampu mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah skenario yg rumit. Sebagai contoh, di level ini seseorang akan mampu memilah-milah penyebab meningkatnya reject, membanding-bandingkan tingkat keparahan dari setiap penyebab, dan menggolongkan setiap penyebab ke dalam tingkat keparahan yg ditimbulkan.
Sintesis (Synthesis)
Satu tingkat di atas analisa, seseorang di tingkat sintesa akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah skenario yang sebelumnya tidak terlihat, dan mampu mengenali data atau informasi yang harus didapat untuk menghasilkan solusi yg dibutuhkan. Sebagai contoh, di tingkat ini seorang manajer kualitas mampu memberikan solusi untuk menurunkan tingkat reject di produksi berdasarkan pengamatannya terhadap semua penyebab turunnya kualitas produk.
Evaluasi (Evaluation)
Dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap solusi, gagasan, metodologi, dsb dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yg ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya. Sebagai contoh, di tingkat ini seorang manajer kualitas harus mampu menilai alternatif solusi yg sesuai untuk dijalankan berdasarkan efektivitas, urgensi, nilai manfaat, nilai ekonomis, dsb
Domain Afektif
Pembagian domain ini disusun Bloom bersama dengan David Krahtwol.
Penerimaan (Receiving/Attending)
Kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di lingkungannya. Dalam pengajaran bentuknya berupa mendapatkan perhatian, mempertahankannya, dan mengarahkannya.
Tanggapan (Responding)
Memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya. Meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam memberikan tanggapan.
Penghargaan (Valuing)
Berkaitan dengan harga atau nilai yang diterapkan pada suatu objek, fenomena, atau tingkah laku. Penilaian berdasar pada internalisasi dari serangkaian nilai tertentu yang diekspresikan ke dalam tingkah laku.
Pengorganisasian (Organization)
Memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik di antaranya, dan membentuk suatu sistem nilai yang konsisten.
Karakterisasi Berdasarkan Nilai-nilai (Characterization by a Value or Value Complex)
Memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah-lakunya sehingga menjadi karakteristik gaya-hidupnya.
2. karakteristik matematika sebagai ilmu terstruktur yaitu maksudnya matematika sebagai ilmu yaitu mempelajari megenai pola keteraturan, tentang struktur yang terorganisasikan. matematika memiliki konsep, dimana konsep tersebut tersusun secara hierarki,logis, dan sistematis, dari konsep yang sederhana hingga yang kompleks. dalam matematika terdapat topik atau konsep prasyarat sebagai dasar untuk memahami konsep selanjutnya, sehingga pembelajaran tersebut menjadi terstruktur. unsur-unsur dalam matematika yaitu unsur yang tidak di definisi (unsur primitif) dan unsur yang terdefinisi.
3. Definisi Aksioma,Postulat,Dalil, dan Teorema.
Aksioma adalah suatu pernyataan yang diandaikan benar pada suatu sistem dan diterima tanpa pembuktian. aksioma hanya memuat istilah dasar dan istilah terdefinisi, tidak berdiri sendiri dan tidak diuji kebenarannya.
Postulat adalah suatu pernyataan yang tidak perlu dibuktikan keakuannya.
Dalil adalah bagian dari teorema.
Teorema adalah suatu pernyataaan matematika yang dirumuskan secara logika dan dibuktikan. teorema terdiri atas hipotesis dan kesimpulan yang dapat dibuktikan dengan memanfaatkan istilah dasar.
4. permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran matematika sekolah yaitu kualitas masukkan sekolah, minat siswa terhadap matematika, kesiapan belajar. Cara mengatasinya yaitu sebagai pendidik dan pengajar kita harus dapat mempertahankanmutu, maksudnya guru sebisa mungkin tidak mudah menyerah untuk senantiasa mengasah anak murid, bagi sekolah menengah yang baru menerima siswa-siswi baru alangkah lebih baik jika mengetahui mutu asal sekolah siswa yang akan mendaftar tersebut. cara mengatasi minat siswa terhadap matematika yaitu kita dapat mengatasinya dengan melakukan melakukan beberapa kegiatan yang tidak hanya di dalam kelas. misalnya kita dapat mengajak peserta didik untuk menghitung luas suatu bangun yang ada disekitarnya. sehingga anak-anak tidak merasa jenuh hanya berada di dalam kelas. Cara untuk mengatasi kesiapan belajar murid yaitu misalnya ketika awal pelajaran, atau sebelum memasuki materi, kita sebagai pendidik dapat memberikan soal-soal dasar pada peserta didik. misalnya ketika hari ini kita akan mempelajari mengenai bangun ruang, sebelum memasuki materi kita dapat menanyakan hal dasar yang berhubungan dengan materi tersebut. misalnya apa bentuk dari balaok dan kubus.
5. Empat tahap perkebangan kogntif individu menurut Piaget yaitu :
a. Tahap sensori motor (Sensory Motor Stage) 0-2 Tahun.
pada tahap ini individu mendapatkan pengalaman dari perbuatan fisik dan koordinasi alat indra. Awalnya pengalaman itu bersatu dengan dirinya, setelah itu dia berusaha mencari objek yang awalnya terlihat, kemudian menghilang dari pandangannya. akhir dari tahap ini yaitu ia mulai mencari objek yang hilang bila benda tersebut tidak terlihat dari perpindahannya. akhirya ia mulai mampu untuk melambangkan objek fisik ke dalam simbol, misalnya mulai bisa berbicara meniru suara binatang.
b. Tahap Pra Operasi (Pre Operasional Strage) 2-7 tahun.
pada tahap ini individu mampu mengklasifikasikan sekelompok objek, menata benda-benda tersebut menurut tempatnya. pada tahap ini pemikiran anak lebih banyak berdasarkan pada pengalaman kognitif daripada logis.
c. Tahap Operasi Konkrit
Pada tahap ini anak sudah berada pada usia Sekolah Dasar. anak-anak pada tahap ini telah memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda yang konkrit. kemmpuan ini terwujud dalam memahami konsep kekekalan, kemampuan untuk mengklasifiksi dan seriasi, mampu memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif, dan mampu berfikir reversibel.
d. Tahap Operasi Formal (Formal Operation Stage)
tahap operasi formal merupaka tahap akhir dri perkembangan kognitif secara kualitas. anak pada tahap ini sudah mampu melakukan penalaran dengan menggunakan hal-hal yang abstrak. penggunaan benda-benda konkret tidak dibutuhkan lagi. anak sudah mampu menalar tanpa harus berhadapan dengan objek atau peristiwa langsung. penalaran yang terjadi dalm struktur kognitifnya telah mampu hanya menggunakan simbol-simbol,ide-ide, abstraksi dan generalisasi. anak sudah memiliki kemampuan-kemampuan untuk melakukan operasi-operasi yang menyatakan hubungan-hubungn, memahami konsep promosi. selain itu pada tahap ini anak telah memiliki kemampuan berfikir kombinatorial. maksudnya kemampuan untuk menyusun kombinasi-kombinasi yang mungkin dari unsur-unsur dalam suatu sistem. misalnya kombinasi warna.
6. Belajar merupakan kegiatan esensial dalam pengajaran, juga terkait dengan berbagai faktor yang dapat memberikan perubahan pada siswa. Faktor siswa, guru serta faktor lingkungan secara menyeluruh merupakan faktor-faktor yang sangat berpengaruh. sedangkan Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.
contoh belajar yaitu ketika seorang siswa sedang membaca buku mengenai gelembung sabun. siswa hanya mengetahui apa itu gelembung sabun tanpa mengetahui hal lain yang berhubungan dengan hal itu. sedangkan contoh pembelajarannya yaitu ketika siswa mencari referensi dari apa gelembung sabun bisa dibuat dan bagaimana prosesnya, disitu siswa mengetahui hal tersebut, ia mulai mencoba untuk mempraktekkan cara membuatnya, setelah itu siswa mengetahui ternyata gelembung sabun terbuat dari sabun dimana sabun terbentuk dari berbagai macam zat.
7. 1 . Teori Thorndike
Edward l. Thorndike (1874-1949) mengemukan beberapa hukum belajar yang dikenal dengan sebutan law of effect. Menurut hukum ini belajar akan lebih berhasil bila respon murid terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Teori belajar stimulus respon yang dikemukakan oleh thorndike ini disebut juga koneksionisme,teori ini mengatakan bahwa pada hakikatnya belajar merupakan proses pembentukan hubungan antara stimulus dan respon. Terdapat beberapa dalil:
a. Hukum Kesiapan (Law Of Readiness)
Yaitu menerangkan bagaimana kesiapan seorang anak dalam melakukan suatu kegiatan. Seorang anak yang mempunyai kecenderungan untuk bertindak atau melakukan kegiatan tertentu dan kemudian dia benar melakukan kegiatan tersebut, maka tindakannya akan melahirkan kepuasan bagi dirinya. Tindakan-tindakan lain yang dia lakukan tidak menimbulkan kepuasan bagi dirinya.
b. Hukum Latihan (Law Of Exercise) dan Hukum Akibat (Law Of Effect).
Hukum latihan menyatakan bahwa jika hubungan stimulus respon sering terjadi, akibatnya hubungan akan semakian kuat. Sedangkan makin jarang hubungan stimulus respon dipergunakan maka makin lemahnya hubungan yang terjadi.
Dalam hukum akibat ini dapat disimpulkan bahwa kepuasan yang terlahir dari adanya ganjaran dari guru akan memberikan kepuasan bagi anak, dan anak cenderung untuk berusaha melakukan atau meningkatkan apa yang telah dicapainya itu. Guru yang memberi senyuman wajar terhadap jawaban anak, akan semakin menguatkan konsep yang tertanam pada diri anak. Kata-kata “ Bagus”, “Hebat” , ”Kau sangat teliti” dan semacamnya akan merupakan hadiah bagi anak yang kelak akan meningkatkan dirinya dalam menguasai pelajaran.
Disamping itu, Thorndike mengutamakan pula bahwa kualitas dan kuantitas hasil belajar siswa tergantung dari kualitas dan kuantitas Stimulus-Respon (SR) dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Makin banyak dan makin baik kualitas S-R itu (yang diberikan guru) makin banyak dan makin baik pula hasil belajar siswa.
Implikasi dari aliran pengaitan ini dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari adalah bahwa:
a. Dalam menjelaskan suatu konsep tertentu, guru sebaiknya mengambil contoh yang sekiranya sudah sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Alat peraga dari alam sekitar akan lebih dihayati.
2. Metode pemberian tugas, metode latihan (drill dan practicc) akan lebih cocok. Karna siswa akan lebih banyak mendapatkan stimulus sehingga respons yang diberikan pun akan lebih banyak.
3. Dalam kurikulum, materi disusun dari materi yang mudah, sedang, dan sukar sesuai dengan tingkat kelas dan tingkat sekolah. Penguasaan materi yang lebih mudah sebagai akibat untuk dapat menguasai materi yang lebih sukar.
2. Teori Skinner
Dalam bagian ini akan diuraikan teori belajar menurut skinner. Burhus Frederic Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting dalam proses belajar. Penguatan dapat dianggap sebagai stimulus positif, jika penguatan tersebut seiring dengan meningkatnya perilaku anak dalam melakukan pengulangan perilakunya itu. Untuk mengubah tingkah laku anak dari negatif menjadi positif, guru perlu mengetahui psikologi yang dapat digunakan untuk memperkirakan dan mengendalikan tingkah laku anak.
Skinner menambahkan bahwa jika respon siswa baik ( menunjang efektivitas pencapaian tujuan) harus segera diberikan penguatan positif agar respon tersebut lebih baik lagi, atau minimal perbuatan baik itu dipertahankan.
3. Teori Ausubel
Teori ini terkenal dengan belajar bermaknanya dan pentingnya pengulangan sebelum belajar dimulai. Ia membedakan belajar menemukan dengan belajar menerima, jadi tinggal menghafalnya. Tetapi pada belajar menemukan konsep ditemukan oleh siswa, jadi tidak menerima pelajaran begitu saja. Selain itu untuk dapat membedakan antara belajar menghafal dengan belajar bermakna.
Pada belajar menghafal, siswa menghafal materi yang sudah diterimanya, tetapi pada belajar bermakna materi yang diperoleh itu dikembangkan dengan keadaan lain sehingga belajar lebih dimengerti. Selanjutnya bahwa Ausubel mengemukan bahwa metode ekspositori adalah metode mengajar yang baik dan bermakna. Hal ini dikemukan berdasarkan hasil penelitiannya. Belajar menerima maupun menemukan sama-sama dapat berupa belajar menghafal atau bermakna.
Misalnya dalam mempelajari konsep Pitagoras tentang segitiga siku-siku, mungkin bentuk akhir c2= b2+a2 sudah disajikan, tetapi jika siswa memahami rumus itu selalu dikaitkan dengan sisi-sisi sebuah segitiga siku-siku akan lebih bermakna.
4 .Teori Gagne
Menurut Gagne dalam belajar matematika ada dua objek yang dapat diperoleh langsung oleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek lansung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan.
Fakta adalah objek matematika yang tinggal menerimanya, seperti lambang bilangan, sudut, dan notasi-notasi matematika lainnya. Kemampuan berupa memberikan jawaban dengan tepat dan cepat,misalnya melakukan pembagian bilangan yang cukup besar dengan bagi kurang,menjumlahkan pecahan,melukis sumbu sebuah ruas garis.
Konsep adalah ilmu abstrak yang memungkinkan kita dapat mengelompokkan objek ke dalam contoh dan noncontoh misalkan konsep, bujur sangkar, bilangan prima, himpunan, dan fektor.
Aturan adalah objek yang paling abstrak yang berupa sifat dan teorema. Menurut Gagne, belajar dapat dikelompokkan menjadi delapan titik belajar yaitu: belajar isyarat , stimulus respon, rangkaian gerak, rangkaian verbal, membedakan, pembentukan konsep, pembentukan aturan, dan pemecahan masalah.
Dalam pemecahan masalah biasanya ada 5 langkah yang harus dilakukan. Yaitu:
1. Menyajikan masalah dalam bentuk yang lebih jelas.
2. Menyatakan masalah dalam bentuk yang lebih operasional.
3. Menyusun hipotesis hipotesis alternattif dan prosedur kerja yang diperkirakan baik.
4. Mengetes hipotesis dan melakukan kerja untuk memperoleh hasilnya.
5. Mengecek kembali hasil yang sudah diperoleh.
2.1.5 Teori Pavlov
Pavlof terkenal dengan teori belajar klasik. Ia melakukan percobaan terhadap seekor anjing, anjing itu dikurung dalam suatu kandang dalam waktu tertentu dan diberi makan. Selanjutnya, setiap akan diberi makan Pavlov membunyikan bel, ia memperhatikan bahwa setiap dibunyikan bel pada waktu tertentu anjing itu mangeluarkan air liurnya, walaupun tidak diberi makanan.
Pavlov mengemukakan konsep pembiasaan atau conditioning. Dalalm hubugannya dalam kegiatan belajar mengajar agar siswa belajar dengan baik maka harus dibiasakan. Misalnya, agar siswa mengerjakan soal peekerjaan rumah dengan baik, biasakanlah dengan memeriksanya, menjelaskannya, atau memberi nilai terhadap hasil pekerjaannya.
6. Teori Baruda
Baruda mengemukakan bahwa siswa belajar itu melalui meniru. Pengertian meniru di sini bukan berarti menyontek, tetapi meniru hal-hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama guru. Jika tulisan guru baik, guru berbicara sopan santun, tingkah laku yang terpuji, menerangkan dengan jelas dan sistematis, maka siswa akan menirunya. Jika contoh yang dilihat kurang baik maka ia pun akan menirunya.
2.1.7 Aliran Latihan Mental
Aliran ini berkembang sampai dengan abad 20, yang mengemukakan bahwa struktur otak manusia terdiri atas gumpalan-gumapalan otot, agar ini kuat, maka harus dilatih dengan beban, makin banyak latihan dan beban yang makin berat,maka otot atau otak itu makin kuat pula, oleh karna itu jika anak atau siswa ingin pandai, maka ia harus dilatih otaknya dengan cara banyak berlatih memahami dan mengerjakan soal-soal yang benar, makin sukar materi itu makin pandai pula anak tersebut.
Struktur kurikulum pada masa itu berisikan materi-materi pelajaran yang sulit, sehingga orang sedikit yang bersekolah karna tidak kuat untuk mengikutinya. Disamping faktor lain seperti keturunan, biaya, dan kesadaran akan pentingya sekolah.
Diposting oleh ratihpenyayangmonyet di 21.31 0 komentar